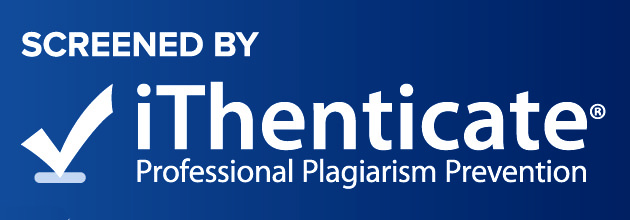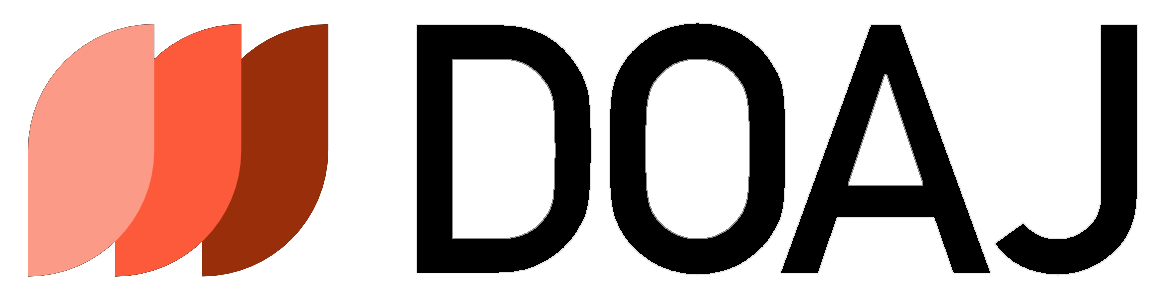RANTAI KOMODITAS, KEWAJIBAN ILMU, DAN SKALA DALAM KONFLIK AGRARIA URUTSEWU
Abstract
Judul: Konflik Agraria di
Urutsewu: PendekatanEkologi
Politik
Penulis: Devy Dhian Cahyani
Penerbit: STPN Press (2014)
Halaman: 251
Tanpa dibayangi rasa sangsi, saya langsung
menyatakan bahwa buku ini sangat berguna. Baik
secara praksis, pun teoritis. Saya bersinggungan
pertama kali dengan naskah Devy kira-kira
setahun yang lalu ketika ia masih dalam bentuk
pdf, naskah skripsi yang sudah diuji. Waktu itu
saya sedang terlibat dalam aliansi Solidaritas
Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus)
dalam persiapan acara Arak-arakan Budaya di
Urutsewu yang sudah dilaksanakan pada 16 April
2014 yang lalu.
Kegunaan praksis buku ini saya rasakan pada
saat itu; bersama dengan beberapa orang warga
Urutsewu (Seniman Martodikromo, Widodo
Sunu Nugroho, dan Ubaidillah) kami menggunakan
skripsi Devy sebagai salah satu sumber
untuk menyusun kronologi konflik tanah yang
sudah sangat panjang di Urutsewu. Kronologi
konflik yang disusun ini, bersama dengan f ile
sikripsi Devy sendiri, kami gunakan sebagai bahan
bacaan di dalam Esbumus agar para personel yang
terlibat dengan segera bisa masuk ke jantung
permasalahan konflik tanah di Kebumen. Karena
terasa betapa jarangnya mahasiswa sekarang yang
melakukan riset konflik agraria, ditambah dengan
kontribusi nyata teks ini yang sudah kami rasakan,
rasa hormat mendalam dihaturkan oleh tulisan
Review Buku
RANTAI KOMODITAS, KEWAJIBAN ILMU,
DAN SKALA DALAM KONFLIK AGRARIA URUTSEWU
Bosman Batubara
Judul: Konflik Agraria di
Urutsewu: PendekatanEkologi
Politik
Penulis: Devy Dhian Cahyani
Penerbit: STPN Press (2014)
Halaman: 251
ini kepada penulis, Devy.
Secara teoritis, saya masih percaya bahwa salah
satu karya tulis ilmiah yang bagus adalah manakala
dia mampu memancing pertanyaan-pertanyaan
di benak pembaca sebagai bahan bagi
penelitian lanjutan. Jadi, meskipun secara personal
saya kadang merasa sayang atau tidak puas
mengingat betapa besar energi yang telah dicurahkan
Devy dalam menggarap penelitiannya
dibandingkan dengan hasil yang ia capai, saya kira
fungsi ketidakpuasan saya adalah memulai
melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk peneliti
selanjutnya.
Dari sisi apa fokus yang diteliti, saya merasa
riset ini hanya membidik realitas secara parsial.
Riset ini dikerangkai secara teoritis untuk mengetahui
ekologi politik konflik tambang pasir besi
di Urutsewu. Tidak ada masalah bagi saya dalam
metode dan metodologi. Masalah muncul di
dalam unit “pasir besi” yang diteliti. Mengapa?
Setelah saya bergulat dengan tema konflik
agraria di Urutsewu, saya tersadarkan bahwa konflik
ini sudah sangat panjang. Berdasarkan kronologi
yang kami susun seperti yang disebutkan di
atas, konflik di daerah pesisir Kabupaten Kebumen
ini merentang sejak 1830-an ketika ada penataan
tanah dalam bentuk Galur Larak yang membagi
tanah dengan sistem membujur utara-selatan.
Sejak itu, berbagai bentuk perampasan tanah
muncul di pesisir Kebumen. Dari situ kita bisa
melihat bahwa pasir besi hanyalah satu komoditas
yang muncul dalam lintasan sejarah. Ada banyak
bentuk masalah yang muncul, misalnya “pemakaian
sebagai lapangan tembak oleh militer;
Bosman Batubara: Rantai Komoditas, Kewajiban Ilmu, dan Konflik ...: 680-683 681
ketakutan masyarakat mengakui bahwa mereka
memiliki sertifikat tanah pasca ’65-66; masuknya
perkebunan tebu Madukismo; pemijaman tanah
untuk uji coba senjata berat; pembangunan jalan
lintas pantai selatan Jawa; penambangan pasir besi;
dan yang paling terkini adalah pemagaran tanah
oleh TNI AD. Dari rentangan kasus-kasus itu
dapat dilihat bahwa pasir besi hanyalah satu
komoditas yang muncul dalam rangkaian proses
panjang pertarungan hakatas tanah, dimana
kondisi kontemporer secara diametral memperhadapkan
massa petani dengan TNI AD, konjungtur
yang bertarung di Urutsewu sekarang ini.
Tanah di Urutsewu berganti fungsi dalam berbagai
bentuk komoditas (perkebunan tebu, jalan,
tambang pasir besi, area latihan tembak) dan
memicu konflik.
Implikasi “kesilapan” memilih unit yang dianalisis
membuat skripsi Devy kurang mampu menangkap
berbagai perubahan ekologi yang terjadi.
Di sini, saya mengandaikan sudah ada kesepakatan
bahwa pengertian ekologi politik memasukkan,
diantaranya, unsur perubahan ekologi
dalam berbagai tingkatan—molekul, struktur
sub-seluler, sel, serabut, organ, organisme, populasi,
komunitas, ekosistem, dan landskap.
Karena unit yang dianalisis buku ini adalah
“ekologi politik tambang pasir besi” yang masih
akan terjadi, maka yang dominan muncul dalam
pembahasan perubahan ekologi politik pada Bab
VI adalah perubahan ekologi (yang juga) akan
terjadi kalau tambang pasir besi dibuka. Dan
dengan memberikan perhatian pada perubahan
yang akan terjadi ini, maka penulis kemudian
banyak meluputkan perubahan ekologi yang
telah terjadi karena konflik panjang, terutama
dengan TNI AD, seperti misalnya, perubahan
organisme karena adanya peristiwa penembakan
pada 16 April 2011 dan ledakan mortir sebelumnya,
serta perubahan landskap karena adanya pembangunan
berbagai ornamen militer di sepanjang
lahan pasir Urutsewu—menara pandang, tempat
peledakan peluru, rumah perlindungan, tempat
uji coba alat berat seperti tank, dan kehadiran
gedung Dislitbang TNI AD itu sendiri di Desa
Setrojenar.
Perubahan-perubahan ekologi tingkat organisme-
landskap seperti yang dipaparkan di atas
tidak mungkin tidak menimbulkan reaksi dari
manusia-manusia yang tinggal di sekitarnya.
Hampir dipastikan pula, sebagai bagian dari aksireaksi
tersebut, muncul satu kebiasaan baru yang
mungkin dalam alunan waktu telah berubah
menjadi ko-evolusi, atau perubahan bersama, baik
di kalangan TNI AD, maupun di kalangan kelompok
yang, untuk menyederhanakan penyebutan,
tertindas seperti petani Urutsewu. Koevolusi
macam apa dan sedalam mana yang telah
muncul, itu yang tetap menjadi misteri. Setidaknya
bagi saya.
Dari analisis seperti di atas, maka ke depan
penelitian yang harus dilakukan adalah melihat
ekologi politik dalam kerangka ruang ekologi dan
waktu. Perubahan-perubahan apa yang terjadi
pada masa Kolonial, Kemerdekaan, Paska Kemerdekaan,
’65-66, Orde Baru, dan Paska Reformasi.
Dengan melakukan studi kronologislah kita akan
dapat melihat semakin jelas tentang kondisi alam,
sosial, serta material praktis yang membentuk
kondisi sosio-alamiah Urutsewu masa kini beserta
semua proses peminggiran yang menyertainya.
Saya tidak bisa memandang enteng naskah ini.
Meskipun, karena itu pula saya merasa tergoda
untuk mempertanyakan arahnya. Sebagai manusia,
saya percaya dengan apa yang saya baca pada
“Konsepsi Kebudjaan Rakjat” bahwa “Kesenian,
ilmu dan industri adalah dasar-dasar dari kebudajaan…
Kesenian, ilmu dan industri baru bisa
menjadikan kehidupan Rakjat indah, gembira dan
bahagia apabila semuanja ini sudah mendjadi
kepunjaan Rakjat.” Apakah naskah Devy ini sudah
menjadi “kepunjaan Rakjat”?
Susah untuk menjawa pertanyaan ini. Namun
saya bisa menghadirkan satu hal yang saya anggap
682 Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
sebagai kebutuhan orang Urutsewu, setidaknya
dalam perspektif subyektif pemahaman saya. Hal
ini penting dimunculkan agar bisa terlihat lebih
terang, apakah naskah Devy ini mengabdi kepada
kepentingan masyarakat. Tentu saja kepentingan
masyarakat di sini lagi-lagi subyektif. Seseorang
bisa mengajak berdebat. Namun, poin yang ingin
saya sampaikan adalah, memberikan sebuah
ukuran terhadap naskah Devy berdasarkan kebutuhan
masyarakat.
Dalam beberapa kali diskusi dengan para elit
gerakan petani di Urutsewu, masalah yang saya
rasa masih sangat susah dipecahkan sampai
sekarang adalah bagaimana menghidupkan
organisasi petani di Urutsewu. Seperti halnya
kebanyakan organisasi petani yang saya lihat—
dan dengar tentangnya—di Jawa Tengah. Saya
sampai pada beberapa poin pemikiran mengenai
organisasi petani di Jawa Tengah, yaitu: 1)memiliki
sifat elitis dalam artian orangnya itu-itu saja dan
dengan demikian isu berputar di kalangan yang
itu-itu juga; 2)hampir tidak ada kaderisasi; 3)tidak
ada agenda organisasi yang disusun bersama,
misalnya agenda tahunan, dan dengan demikian
tidak ada rapat-rapat kontinu; serta 4)kurang
berdikari di bidang ekonomi.
Naskah Devy ini, kita sadari atau tidak, belumlah
menyentuh apa yang saya anggap sebagai
kebutuhan organisasi petani di atas. Dia baru
menyentuh dan mengantarkan pembaca ke “halaman”
permasalahan-permasalahan itu. Jadi,
seandainya waktu bisa diputar mundur dan saya
ditakdirkan menjadi kawan diskusi Devy dalam
proses penyusunan skripsinya ini, maka saya akan
dengan sangat bersemangat menyarankan dia
melakukan penelitian mendalam terhadap
“ekologi politik-mikro organisasi petani di
Urutsewu,” agar hasilnya juga menjawab permasalahan/
kebutuhan organisasi petani seperti yang
saya sampaikan di atas. Andai itu terjadi, sependek
yang dapat saya pahami, teks ini akan semakin
bernas baik secara teoritis maupun praktis.
Dari segi ekologi politik tambang pasir besi,
saya merasa Devy melewatkan satu hal dengan
tidak membahas konteks global dan nasional
surutnya perusahaan pasir besi di Urutsewu
dengan dicabutnya perizinan oleh TNI AD pada
Mei 2011. Dalam konteks global, tentu saja ini tidak
bisa dipisahkan dari kecenderungan menurun
harga bijih besi di pasaran dunia. Pada awal 2011
bijih besi memiliki harga sekitar 175 Dollar AS per
ton, dan kecenderungan turun terus terjadi
hingga menginjak harga sekitar 80 Dollar AS per
ton pada medio 2014 (sumber:
chartbuilderinfomine.com). Hal seperti ini juga
terjadi dengan ledakan permintaan komoditas
mangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada
periode 2008-10 dan kemudian menyusut seiring
dengan menurunnya harga mangandunia dan
turunnya pertumbuhan ekonomi China ke bawah
9%, setelah sebelumnya selama sepuluh tahun
pada periode 2002-12 konsisten di atas 9%. Dalam
konteks ini, China adalah tujuan ekspor mangan
NTB.
Di tingkat nasional, ini tentu saja tak bisa
dipisahkan dari konteks regulasi UU Minerba 4/
2009 yang mewajibkan pembangunan pemurnian
(smelter) untuk sektor industri ekstraktif. Meskipun
kemudian hal ini dianulir kembali melalui
Peraturan Pemerintah (PP) 1/2014 yang menurunkan
konsentrasi bijih ekstraksi yang dapat
dieksport. Sebagai contoh, untuk pasir besi (jenis
pig iron) pada Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral(Permen ESDM) 7/2012
yang merupakan “cucu” UU 4/2009 disebutkan
pasir besi boleh dieksport dengan konsentrasi
kemurnian lebih dari 94% Fe; dan pada Permen
ESDM 1/2014 (“anak” dari PP 1/2014) dia diturunkan
menjadi e” 58% Fe.
“Penganuliran” ini adalah hal yang lain, yang
penting diperhatikan di sini adalah kewajiban
peningkatan nilai tambah komoditas ekstraksi
dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pembangunan
smelter telah membuat dinamika
Bosman Batubara: Rantai Komoditas, Kewajiban Ilmu, dan Konflik ...: 680-683 683
industri ekstraksi berubah ke arah ketakutan
kalangan industri tidak mampu memenuhi
kualif ikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
melalui UU Minerba 4/2009 (dan peraturan turunannya)
sebelum ia kemudian dianulir seperti
yang dijelaskan di atas.
Poin saya membawa dua variabel global dan
nasional ini, sebagai tambahan terhadap angka
kebutuhan besi yang tinggi dan disebut sebagai
pemicu munculnya berbagai Izin Usaha Pertambangan
pasir besi di Indonesia oleh Devy, ingin
menunjukkan bahwa logika yang sama bisa ditautkan
mengapa aktivitas ini menyurut belakangan.
Tentu saja tanpa menapikan bahwa ada
perlawanan di tingkat lokal seperti yang digalang
berbagai kelompok petani di Urutsewu. Dengan
demikian, kita bisa melihat lebih jelas antara
hubungan “skala” global, nasional, dan lokal dalam
rantai produksi komoditas pasir besi, atau yang
oleh Devy disebut sebagai kapitalisme global.
Untuk menyimpulkan sumbangan teoritis
buku ini, dengan demikian, adalah kemampuannya
memicu pertanyaan tentang: 1)politik ekologi
konflik agraria di Urutsewu dalam rentang temporal
yang lebih panjang (sejak 1830-an) hingga
sekarang dalam berbagai bentuk eskalasi—deeskalasinya
karena perubahan komoditas; 2)
memetakan kebutuhan yang lebih konkret organisasi-
organisasi petani dengan mengasumsikan
bahwa ilmu seharusnya adalah “kepunjaan Rakjat”;
dan 3)memperlihatkan secara gamblang hubungan
“skala” (global, nasional, dan lokal) dalam
rantai produksi komoditas. Dan rasanya, inilah
tugas peneliti berikutnya.